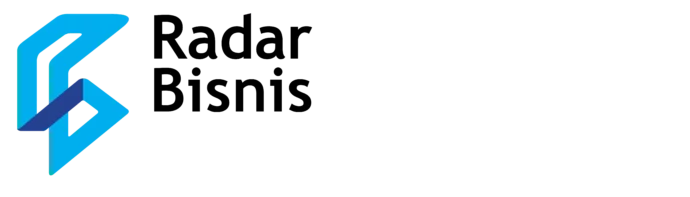Oleh: Sugeng Winarno, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang.
Oleh: Sugeng Winarno, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang.
BULAN Ramadan telah menjadi ajang pertemuan antara budaya masjid dan budaya pasar di televisi (TV). Beragam acara yang bernuansa masjid seperti ceramah agama, talkshow bertema Islam, kajian kitab dan hadis, lomba dai, dan majelis taklim setiap hari muncul di TV. Pada saat yang sama, di TV juga muncul budaya pasar lewat berbagai program hiburan yang sarat dengan iklan yang mengajak orang berbelanja layaknya di pasar.
Menurut Kuntowijoyo, ada dua budaya, yakni budaya masjid dan budaya pasar. Budaya masjid menggambarkan religiusitas dan jauh dari sifat foya-foya. Sementara budaya pasar adalah budaya yang penuh dengan tipudaya dan lebih mementingkan materi. Praktik sejumlah media TV telah membawa pada budaya pasar. Komersialisasi media telah merepresentasikan agama dalam ruang profan dan hedonis.
Lihat saja acara Ramadan di sejumlah stasiun TV. Beberapa acara yang menghadirkan para penceramah sering dibalut dalam kemasan komedi. Munculnya beragam acara jelang waktu sahur dan berbuka puasa yang menghadirkan para komedian justru sering menampilkan lelucon yang mengumbar kekerasan, seksualitas, dan sarkasme. Komedi model lelucon kasar (slapstick) justru banyak didemonstrasikan di TV selama Ramadan.
Tak jarang justru sang penceramah terbawa pada suasana lucu yang lebih dominan ketimbang isi ceramah yang bermutu. Beberapa pendakwah yang muncul di TV sekaligus menjadi bintang iklan produk tertentu. Bahkan, tak jarang busana dan beragam aksesori yang dikenakan para penceramah itu di endorse merk tertentu. Dalam penampilan sang penceramah dan pengisi acara bernilai promosi produk tertentu. Di sinilah letak persoalan yang bisa bernilai negatif bagi masyarakat.
Logika TV
Acara Ramadan di TV dari tahun ke tahun cenderung serupa. Acara selalu berulang dengan kemasan yang sama. Tak semua acara dikemas dengan isi yang sejalan dengan nilai-nilai Ramadan. Media audio visual TV ini seperti sekadar memanfaatkan momentum Ramadan untuk mendulang banyak iklan. Ya, inilah logika TV. Karena TV (terutama TV swasta) adalah entitas bisnis, maka logika yang dipakai adalah bagaimana mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya.
Perilaku sejumlah media TV saat Ramadan ini sah-sah saja sebagai lembaga profit. Namun, hendaknya tak ada yang jadi korban dalam praktik ini. Masyarakat luas, para konsumen media idealnya menjadi perhatian utama. TV tak bijak kalau hanya merayu dan memberi iming-iming khalayak agar menonton acara, namun kemanfaatan dari acara itu justru berdampak buruk bagi pemirsa.
Logika yang idealnya dibangun oleh TV adalah menempatkan masyarakat sebagai khalayak yang harus diberdayakan, diberi pendidikan dan pencerahan, agar TV juga menjalankan fungsi sebagai sarana untuk mencerdaskan umat. Namun, beberapa pengelola TV selama Ramadan terlihat lebih memilih menjadikan momentum bulan Bulan Suci ini sebagai komoditas yang digunakan untuk merayu penonton agar konsumtif.
Logika TV menjadikan segala sesuatu sebagai materi yang layak jual, termasuk agama. Di sinilah proses komodifikasi terjadi. Komodifikasi berarti mengubah agama menjadi barang dagangan yang dapat dijual, membawanya ke cara transaksi dagang layaknya di pasar. Lewat acara Ramadan tak jarang muncul tren baju koko dan model hijab atau busana muslim para ustadah. Tak jarang para muslim menggunakan produk-produk seperti yang dikenakan para penceramah karena beranggapan bahwa hal itu sebagai bentuk perwujudan keimanan.
Komodifikasi Ramadan
Agama dan hal-hal yang terkait dengan agama, seperti Ramadan telah menjadi sebuah komoditas. Seperti layaknya komoditas barang dan jasa, maka sebuah komoditas pasti mempunyai nilai jual yang bisa digunakan untuk mendapatkan keuntungan. Di sinilah Ramadan telah dipandang sebagai komoditas dan TV telah melakukan komodifikasi atas agama dan Ramadan.
Lihat saja acara-acara pengajian dalam kemasan majelis taklim. Acara dikemas dengan unsur hiburan yang lebih menonjol. Majelis taklim itu dikemas jadi “Taklimtainment”. Sebuah majelis taklim yang disajikan dengan balutan hiburan (entertainment) yang kental. Tak jarang justru muatan hiburannya yang lebih kentara ketimbang esensi dakwahnya. Esensi taklim sebagai sarana pengajaran agama Islam telah terdistorsi karena unsur hiburan yang lebih mengemuka.
Budaya konsumtif justru muncul dari acara-acara yang bersifat keagamaan. Terjadi paradoks antara konten pesan-pesan dakwah keagamaan yang dituturkan para penceramah dengan pesan-pesan lain yang melekat dalam diri dan perilaku sang dai. Di satu sisi para penceramah menganjurkan hidup sederhana dan tak bermewah-mewah, sementara pada kesempatan yang sama seperti menganjurkan agar masyarakat membeli produk-produk iklan yang lagi tayang.
Inilah tantangan dakwah di era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang supercanggih saat ini. Format dakwah di TV yang ideal perlu terus dicari. Jangan sampai terjadi seperti apa kata pepatah Jawa kuno yang mengatakan “Sesuk in akhire zaman, tuntunan dadi tontonan, lan tontonan dadi tuntunan”. Mari bermedia yang sehat, jangan telan mentah-mentah budaya masjid yang telah bercampur dengan budaya pasar yang muncul di layar TV. (*)