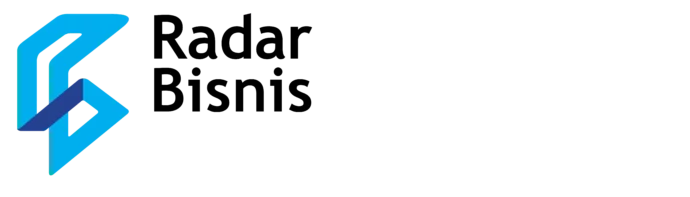Oleh: Dwi Setiyawan, Wartawan Jawa Pos Radar Tuban
Oleh: Dwi Setiyawan, Wartawan Jawa Pos Radar Tuban
AWAL 2010, Komisi C DPRD Blora geram dengan banyaknya tower pemancar base transceiver station (BTS) di kawasan kotanya. Mereka meradang karena keberadaan menara pemancar sinyal tersebut memicu peningkatan intensitas petir yang menyambar kawasan kota.
Saya yang ketika itu masih bertugas di Kota Sate tersebut sangat tertarik untuk menggali sejauhmana keberadaan tower menarik petir. Karena itu, saya begitu concern mengikuti semua wacana pertoweran yang bergulir di gedung parlemen tersebut.
Sebenarnya, di tahun tersebut keberadaan tower provider di Kota Blora tak sebanyak di Tuban saat ini. Kawasan perkotaan Bumi Ronggolawe sekarang ini bak ”hutan pemancar” dengan pohon-pohon tower yang menjulang. Dari sisi sensitivitas saat itu, harus diakui wakil rakyat di Blora lebih peka. Sebelum wilayah kotanya menjadi ”hutan pemancar”, mereka sudah mengantisipasi jauh hari sebelumnya. Kalau perlu menghadang pendirian tower berikutnya.
Tak hanya melarang, komisi ini juga merumuskan rencana memindahkan sekitar seratus lebih tower yang tersebar di Blora ke kawasan pegunungan Semanggi, Desa Semanggi, Kecamatan Jepon. Pertimbangannya, kalau tower dilokalisir di sebuah daerah, maka akan lebih aman dan tidak merugikan masyarakat. Mereka mencontoh penataan tower di Semarang yang dilokalisir di kawasan Pegunungan Gombel.
Terlepas apakah rencana tersebut sekarang ini membawa hasil, yang pasti niat wakil rakyat Blora untuk menyelamatkan kotanya dari tingginya intensitas petir yang nyambangi kotanya patut diapresiasi.
Dari komisi ini pula saya belajar banyak tentang petir. Meski tidak mengikuti konsultasi langsung anggota komisi ini dengan sejumlah pakar yang ditemui, saya mendapat kesempatan untuk mempelajari resume dari pertemuan tersebut. Salah satunya dari penjelasan ahli meteorologi dan geofisika Semarang. Meski lupa menulis nama pakar tersebut, file saya masih menyimpan lengkap.
Menurut penjelasan pakar tersebut, petir adalah gejala alam akibat perbedaan potensial antara awan dan bumi yang cukup besar saat hujan. Saat petir menyambar terjadi pembuangan muatan negatif (elektron) dari awan ke bumi dengan media penyalur adalah udara. Saat hujan, udara mengandung kadar air yang lebih tinggi, sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir.
Saat menyalur melalui media udara inilah, petir cenderung mencari penghantar benda yang permukaannya lebih tinggi dan berujung runcing atau lancip. Benda yang paling potensial tersebut adalah tower. Sayangnya, ketika itu tingginya intensitas petir, sebagaimana dipaparkan legislator tersebut tanpa didukung data rinci jumlah petir yang menyambar setiap hujan. Juga data pembanding sebelum berdiri tower.
Hanya dipaparkan tingginya intensitas petir yang menyambar ke kawasan pemukiman sangat merugikan warga. Khususnya peternak ayam potong yang hewan piarannya rentan mati karena stres dengan gelegar suara tersebut. Kerawanan lain adalah rusaknya perangkat elektronik. Terlebih, kalau petir tersebut menyampar kabel listrik PLN yang grounding-nya tidak begitu kuat. Dalam sejumlah kasus di Tuban, justru PLN beberapa kali kehilangan kabel grounding-nya yang dicuri. Kerugian lain adalah kerawanan bila tower tersebut runtuh akibat teraliri petir dan bahaya petir itu sendiri bagi manusia.
Kembali mengutip penjelasan pakar meteorologi dan geofisika, kawasan yang beberapa kali disambar petir cenderung menjadi langganan tetap media lompatan elektron listrik petir. Sebab, tingkat kenetralan tanah semakin tinggi. Kondisi ini merangsang petir untuk menyalur di daerah tersebut berulang kali setiap hujan.
Apakah setelah kawasan Kota Tuban menjadi ”hutan pemancar” kerawanan yang dipicu akibat petir yang sering nyambangi benar-benar terjadi? Ini yang sampai sekarang belum kita dengar. Apakah kita harus menunggu dampak kerawanan yang sangat merugikan tersebut sampai ”hutan pemancar” di Bumi Ronggolawe lebih lebat? (*)