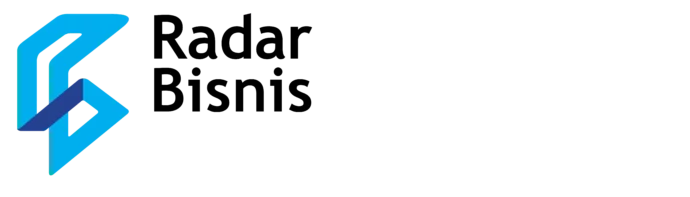“Tunggu sampai bulan muncul, setelah itu akan kukatakan aku mencintaimu.”
Pria yang telah lama kukagumi meneleponku pagi ini. Suaranya sedikit berat membuat degup jantungku meningkat.
 Ada apa ini? Sedari tadi pikiranku tak henti menerka apa yang mungkin terjadi. Apakah penantianku terbalas? Mustahil. Apa dia akhirnya lelah, lalu menyerahkan hatinya padaku? Ah, malu membayangkan hal itu.
Ada apa ini? Sedari tadi pikiranku tak henti menerka apa yang mungkin terjadi. Apakah penantianku terbalas? Mustahil. Apa dia akhirnya lelah, lalu menyerahkan hatinya padaku? Ah, malu membayangkan hal itu.
Aku dan dia bertemu tanpa sengaja, pada siang yang buru-buru di sebuah tikungan. Menyebut itu pertemuan indah agaknya kurang pas, sebab aku membuat setir motornya bengkok. Ketika hendak berbelok, mobilku tak sengaja menabrak motornya, mungkin menyenggol kata yang lebih tepat.
Ya, kuakui hari itu belum genap 24 jam setelah aku belajar menyetir mobil. Masih jelas dalam ingatan, aku segera keluar dari mobil dengan perasaan khawatir, buru-buru menghampiri.
Dia berusaha berdiri, melepas helm lalu memandangku yang sedang berjalan ke arahnya. Itulah detik terindah pada cerita ini.
“Aku tidak apa-apa, oh maksudku, kamu tidak apa-apa?” tanyaku gugup saat itu.
“Tidak, kalau kamu?” tanyanya balik.
“Iya, aku apa-apa.” Jantungku berdebaran tak tahu malu. Kata yang keluar dari mulutku bahkan tak lolos gramatikal.
Aku tahu itu bukan waktu yang tepat menanyakan alamat atau nomor Whatsapp. Ada perasaan yang diam-diam bersemayam. Dan sulit dilupakan—ah, kenapa tampan sekali?
Pertemuan tak sengaja itu membawa kesengajaan berikutnya. Sengaja menantinya di tikungan pukul 2 siang. Jika belum beruntung, besoknya ke sana lagi.
Dan keberuntungan itu pun tiba. Aku mengikutinya, ternyata aku dan dia mahasiswa di kampus yang sama.
Penasaran namanya? Maaf, aku tidak bermaksud memberi tahu, nanti makin banyak yang mengaguminya selain aku.
Aku menyukai kata-katanya. Diksiku sering kali habis ditelan rasa malu-malu. Meski aku tahu, kata-katanya sekadar menghiburkan, tetap saja itu bikin candu.
Suatu pagi.
“Antara kopi dan teh, mana yang lebih kamu suka?” tanyaku.
“Kopi.”
“Kenapa?”
“Kopi tahu dirinya pahit, namun tetap banyak yang menyukainya.”
“Mirip kamu.”
“Berarti banyak yang menyukaiku dong?”
“Ih kepedean!”
“Ya, maksudnya gimana?”
“Kamu tidak bisa ditunggu, tetapi aku terus menunggumu.”
“Bukan, begitu ehm…”
Kalimatnya terputus, mungkin dia bingung mengeja kata-kata, atau sedang memilih tanda baca agar maknanya bisa diterima rasa.
“Kalau gitu aku akan menyeduhkan kopi setiap hari untukmu,” lanjutku.
“Kenapa?”
“Biar aku lebih mengerti pahit kopi,” jawabku lebih serius.
“Kopi itu meski pahit, dia tidak pura-pura.”
Dan aku terus menunggunya, bersama ketidakpura-puraannya.
Sedetikpun aku tidak ingin berpaling, tidak ingin penantian ini berakhir asing. Aku ingin membuatnya tinggal, bukan sekadar hadir karena takdir menyuruhnya mampir.
Cerita ini cenderung melodrama, memang begitulah adanya. Aku dan dia mengenal lama, sering makan berdua, ke mana-mana juga berdua, bicara sedari pagi hingga malam sudah biasa.
Tapi aku tidak tahu seperti apa isi hatinya. Pernah aku bertanya jawabnya sekadarnya bahkan terkesan bercanda.
Temanku bilang aku bodoh—mungkin—aku menunggu pria selama lima tahun. Aku pernah mengungkapkan cintaku, dia jawab “Oh, iya” begitu saja.
Mungkin saat itu kalimatku terlalu rumpang, hingga jawabnya asal rampung.
Aku juga pernah bilang, “Aku akan menunggumu mencintaiku,” ucapku, suatu kali.
Aku tahu dia mendengarnya di balik kesibukan bergelut ekonomi mikro di ruang kerjanya.
Perlu kuberitahu, dia yang kujatuh cintai itu selalu tampak memikat saat sedang serius bekerja, dengan memakai kacamata minusnya sembari fokus menatap layar laptop, sesekali menyibak rambut yang menghalangi pandangannya.
Penantian ini bagai keseharian yang entah sampai kapan. Batas pantas antara aku dan dia rasa-rasanya semakin jauh saja.
Jika benar kata temanku, sebaiknya aku memilih berhenti dan mulai mencari arti—diriku. Akan tetapi, aku sendiri tak punya arti, seperti afiks yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa sebuah kata.
Bagiku, dia adalah kata, aku butuh dirinya untuk membuatku sempurna dan bermakna.
Aku pernah ingin berhenti menunggunya, tetapi bagaimana sebuah afiks tanpa kata? Di mana-mana imbuhan butuh kata untuk melengkapinya.
Sifat afiks itu terikat, sama halnya diriku yang terikat olehnya sejak pertama berjumpa.
Dia adalah kataku, yang menjelaskan tentang arti mencinta dan menunggu adalah hal biasa. Aku tanpa dia kosong tak bermakna.
Aku tidak ingin kalah dengan rasa bersalah karena lelah. Perkara cinta ini biarkan saja tanpa terjemah, asal tidak lemah dan membuatku ingin menyerah.
Masih empat jam lagi, pikiranku tak bisa diajak kompromi, aku mondar-mandir depan cermin
Memilih baju ternyata sesulit ini, serasa tidak ada yang cocok meski seisi lemari sudah kucoba.
Setelah perdebatan batin yang panjang, aku menjatuhkan pilihan pada gaun putih dengan sedikit renda di bagian bawah.
***
Iringan musik akustik samar-samar terdengar, aku melihat sekeliling, tempat itu tampak sepi, pelayan cafe mengarahkanku ke dekat pohon dengan hiasan lampu, di sebelahnya tertata sebuah meja dan dua kursi bernuansa putih. Di tengah meja itu ada lilin dan vas bunga kecil.
Aku mendongkak ke atas, langit sudah gelap dan bulan cantik memperindah pemandangan malam.
Pikiranku masih belum bisa menerka apa yang sedang terjadi. Dan di mana dia? Dia hanya menyuruhku datang lebih dulu, tanpa banyak bertanya aku mengiyakan.
Tetiba dari arah depan, pria yang kukagumi datang, dia berjalan ke arahku membawa buket bunga mawar segar, seperti ada percikan sihir yang pelan-pelan memenuhi badan seiring langkahnya semakin dekat.
“Happy anniversary 5 tahun istriku. Maaf, aku telat membawakan cintaku,” katanya berbisik, membuat jantungku berisik. Mungkin didengar bulan malam ini. (*)