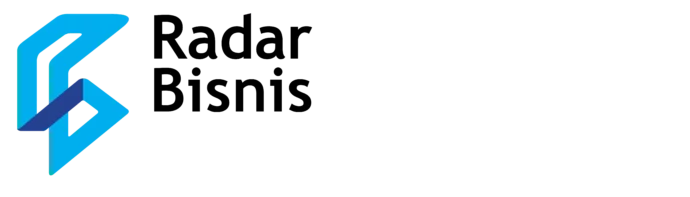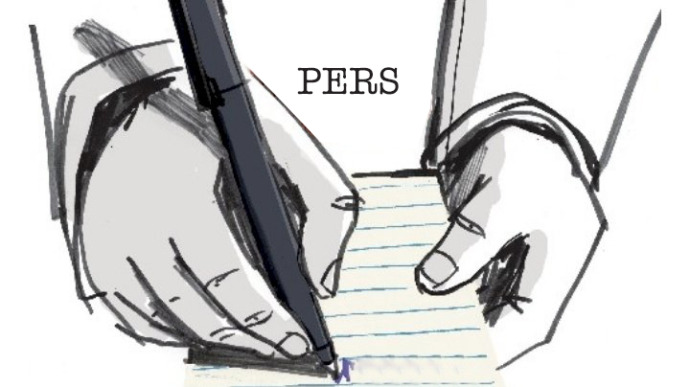Oleh: Ahmad Atho’illah, wartawan Jawa Pos Radar Tuban
KEINGINAN saya menjadi wartawan datang begitu saja. Sedikit pun tak ada rencana, apalagi cita-cita. Semua berangkat dari hobi membaca koran di sebuah perpustakaan. Sekitar 12 tahun lalu. Semasa masih duduk di bangku kuliah.
Dari situ, saya membayangkan—profesi wartawan itu sangat menyenangkan. Mencari berita dan bisa bertemu banyak orang dan menambah jaringan. Satu lagi, profesi yang sering dijuluki kuli tinta ini juga sangat keren. Setidaknya, itu menurut saya. Bagaimana tidak, jika umumnya orang bekerja sudah tahu apa yang akan dikerjakan, tidak demikian halnya dengan profesi wartawan. Bekerjanya dari sebuah ide yang tidak berbentuk. Ketika seorang wartawan akan menulis berita, hanya bayangan ide yang ada. Tidak jelas, abstrak. Tidak berwujud.
Namun, puzel-puzel itu harus tersusun rapi menjadi sebuah kabar informasi. Mulai membuat judul, menyusun lead, memasukan unsur 5W1H (what, where, why, when, who, dan how) menjadi sebuah kalimat, hingga menghasilkan sebuah tulisan yang enak dibaca. Keren bukan?
Sesederhana itu saya membayangkan. Hingga akhirnya kesempatan itu datang. Seorang kawan memberikan informasi perusahaan media Jawa Pos Radar Bojonegoro membuka lowongan kerja untuk posisi wartawan.
Awalnya saya sempat bimbang. Antara keinginan dan rasa kurang percaya diri sepertinya tidak imbang. Lebih berat mindernya daripada keinginan. Maklum, saya sangat minim pengalaman. Hanya mahasiswa pendidikan agama Islam (PAI). Setelah melalui perenungan, akhirnya niat saya menjadi wartawan sangat bulat. Seluruh persyaratan saya siapkan untuk berangkat menjemput impian.
Singkat perjalanan, selama menjadi wartawan Jawa Pos Radar Bojonegoro, saya memperoleh banyak pelajaran dan pengalaman. Di sisi lain, saya hampir menyerah dengan profesi ini. Sebab, profesi wartawan ternyata tidak seperti yang saya bayangkan—tentang yang indah-indah. Bertemu banyak orang, memiliki banyak jaringan, dan memiliki privilege yang keren.
Dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022, sebagian pelajaran hingga pengalaman pahit tersebut saya tuangkan dalam tulisan refleksi.
Wartawan Tidak Boleh Salah
Saya masih ingat, waktu itu jarum jam sudah menunjukkan pukul 21.00. Tugas ngetik berita selesai. Namun, ada semacam aturan yang tidak tertulis bagi wartawan baru. Memang tidak mengikat, tapi wajib ditaati jika tidak ingin kebawa mimpi. Aturannya, wartawan baru dilarang pulang sebelum redaktur selesai ngedit berita yang dituliskan wartawan.
Setiap malam sehabis ngetik, saya duduk-duduk di belakang ruang redaksi sembari menunggu waktu dipanggil redaktur untuk klarifikasi atas berita yang saya tulis. Tak jarang, panggilan redaktur itu sangat mengagetkan. Bukan nadanya yang keras dan melengking tajam, melainkan saya saja yang kagetan.
”Tok, kamu ini bagaimana? Nulis berita tapi tidak ada konfirmasinya. Tidak bisa seperti ini, bisa dituntut kamu. Berita itu harus berimbang (cover booth side). Cari konfirmasi,” tegur redaktur. Perintah itu meluncur begitu mengagetkan bagi wartawan baru seperti saya. Apalagi, waktu itu sudah menunjukkan pukul 21.00. Waktu yang sudah larut malam. Namun, tidak ada alasan untuk tidak menjalankan perintah redaktur. Toh, semua itu juga untuk kebaikan saya sendiri. Sebab, sangat mungkin berita yang saya tulis akan berakhir dengan gugatan—tuntutan, karena dianggap tidak berimbang. Karena itu, meski sudah larut malam, konfirmasi tambahan tetap harus saya dapatkan. Jika tidak, maka berita yang saya tulis tidak akan ditayangkan. Itulah tanggung jawab seorang jurnalis.
Sekali tayang, tidak bisa ditarik ulang. Karena itu, semua berita yang esok terbit harus sesuai dengan kaidah jurnalistik dan bisa dipertanggungjawabkan, baik data maupun faktanya. Lebih baik mengantisipasi daripada berakhir dengan salah persepsi.
Tak hanya tak boleh salah. Benar pun terkadang wartawan masih dianggap salah. Hal ini sudah biasa.
Wartawan Tak Boleh Lelah
Masih teringat jelas pengalaman waktu itu. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Waktu itu, saya sudah ditugaskan di Tuban. Menjelang tengah malam itu, saya sudah pulang. Rumah saya di perbatasan Tuban-Lamongan di bagian utara. Baru hitungan menit membaringkan badan, ponsel berdering memberikan kabar yang sungguh tidak diharapkan; kabar kecelakaan kontainer. Lokasinya, di perbatasan Tuban-Lamongan wilayah selatan, tepatnya di Kecamatan Widang. Waktu itu, sulit mengambil keputusan, antara berangkat liputan atau tetap bertahan membaringkan badan. Yang sulit dalam mengambil keputusan bukan soal tugas peliputan, melainkan jarak tempuh yang sangat jauh. Perbatasan Tuban-Lamongan di wilayah selatan itu bisa ditempuh dari perbatasan Tuban-Lamongan utara. Namun, di tengah malam itu sangat tidak mungkin saya lakukan. Sebab, jalur yang harus dilalui adalah hutan. Karena tidak ada pilihan lain, saya pun memutuskan mencari rute yang aman. Memutar ke arah Tuban kota. Baru setelah itu menuju lokasi kejadian di Widang. Sangat berat, namun tetap harus saya lakukan.
Seingat saya, sampai lokasi tepat tengah malam. Setelah satu jam liputan, saya kembali pulang. Kurang lebih pukul dua dini hari baru tiba rumah. Lelah selelah-lelahnya. Apakah tugas selesai? Belum. Ini baru proses peliputan. Kejadian di lokasi harus disusun menjadi sebuah berita.
Seperti itulah profesi wartawan yang oleh kebanyakan orang dianggap mudah, ringan, dan menyenangkan. Tidak salah, muncul sebuah kredo: Wartawan tidak boleh salah dan lelah.
Jika perjalanan seorang wartawan dituliskan secara lengkap, sangat panjang dan memakan banyak halaman. Karenanya, pengalaman pahit yang lain biar saya saja yang menyimpan. Pun sesekali yang menyenangkan. (*)