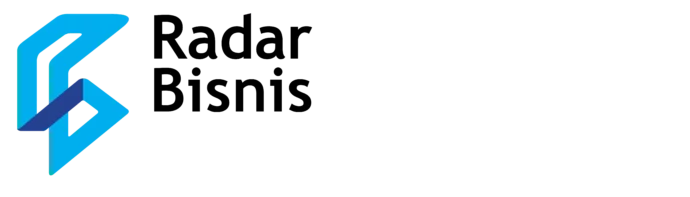Setelah melalui proses dinamika politik dan tahapan pemilu yang cukup panjang. Rabu (14/2) besok, saatnya kita semua menuju tempat pemungutan suara (TPS) untuk menentukan pilihan.
Sebab, demokrasi memberikan hak kepada kita semua untuk menentukan pilihan.
 Karena itu, pilihlah calon pemimpin berdasar kesadaran—yang kita anggap baik dan layak memimpin negeri ini.
Karena itu, pilihlah calon pemimpin berdasar kesadaran—yang kita anggap baik dan layak memimpin negeri ini.
Bukan berdasar gimik, apalagi money politics.
Melalui kolom yang tidak panjang ini, penulis ingin mengajak pembaca untuk berefleksi.
Kita semua sadar, pada kepentingan pribadi, manusia selalu berpikir idealis dan realistis.
Ketika sakit dan ingin berobat, misalnya, naluri manusia selalu mencari refrensi dokter terbaik.
Ada perasaan enggan jika ditangani dokter yang tidak berpengalaman. Apalagi dengan track record yang tidak meyakinkan.
Pun demikian dalam hal pendidikan. Sebelum menentukan pilihan, terlebih dulu mencari refrensi—membandingkan kualitas setiap lembaga pendidikan.
Pada urusan yang paling personal—mencari pasangan, juga tidak lepas dari pertimbangan-pertimbangan rasional, bibit, bebet, dan bobot.
Tidak jarang sepasang kekasih memutuskan berpisah karena tidak memenuhi perhitungan standar rasional.
Lantas, kenapa manusia sering menghilangkan rasionalitas ketika dihadapkan pada pilihan politik.
Jika kita tidak akan menunjuk pilot kapal dari seorang yang tak memiliki pengetahuan ihwal perpilotan dan rute yang akan dilalui, mengapa kita menunjuk penguasa negara dari orang yang tidak memiliki pengetahuan dalam bernegara.
Mengapa kita memilih calon presiden, calon anggota DPR, calon gubernur, calon bupati hanya berdasar perhitungan pragmatis.
Dan, lebih parah lagi—memilih berdasar money politics.
Pilihan ditentukan hanya berdasar nominal rupiah yang diberikan. Kenapa naluri rasionalitas kita sebagai manusia tetiba menjadi kontradiktif—transaksional ketika dihadapkan pada pilihan politik.
Apa yang menyebabkan itu semua? Uang.
Ya, uang sering kali membuat seseorang hilang kesadaran.
Dan ini bukan hal baru dalam kehidupan manusia.
Yuval Noah Harari, dalam bukunya yang berjudul Sapiens, menulis, sejak ribuan tahun yang lalu—sebelum manusia saling perang dan teknologi berkembang pesat seperti sekarang, para filsuf, pemikir, dan nabi telah mencela uang.
Mereka menyebut bahwa uang adalah sumber dan akar kejahatan.
Uang yang dulunya berfungsi sebagai medium pertukaran universal—untuk memudahkan manusia mendapatkan sesuatu yang dinginkan, kini telah melebihi batas fungsinya.
Uang telah menjelma menjadi sesuatu yang sangat berkuasa.
Setiap orang nyaris bisa mendapatkan segala hal yang diinginkan ketika memiliki banyak uang.
Dan setiap orang nyaris bersedia melakukan apa pun itu, asal mendapatkan uang.
Uang yang sesungguhnya hanya produk psikologi manusia, kini telah bekerja melewati batas fungsi.
Uang tak lagi menjadi sistem kesalingpercayaan antarmanusia dalam menukar barang.
Pada hal yang positif, uang mampu mengubah orang yang dulunya bodoh menjadi pintar karena mampu membayar biaya pendidikan, dan yang sakit menjadi sembuh ketika sesorang mampu membayar biaya rumah sakit.
Namun, pada taraf yang negatif, uang juga bisa mengubah segalanya. Seseorang yang melakukan kejahatan bisa lepas dari jerat hukum ketika mampu membayar pengacara dan menyogok hakim.
Dengan suap—uang pelicin, seseorang bisa dengan mudah “membeli” jabatan.
Ketika memiliki banyak uang, negara bisa membeli begitu banyak persenjataan untuk menjajah dan memerangi negara lain yang lemah.
Dengan uang pula, seseorang bisa membeli kekuasaan. Uang tak lagi sebagai sistem kesalingpercayaan.
Demi kekuasaan, uang bisa dengan mudah membeli kepercayaan. Dan, money politics adalah gambaran.
Sudah sering kita mendengar adagium: jika tidak memiliki banyak uang, maka jangan coba-coba mencalonkan diri—bersaing merebutkan kekuasaan.
Lantas, di mana batas uang? Jawabannya pada prinsip dan hal-hal yang tidak ternilai.
Yakni, moral, kehormatan, kesetiaan, dan cinta.
Ketika moral, kehormatan, kesetiaan, dan cinta bisa dibeli dengan mudah, maka tak ada lagi yang tersisa. Manusia telah melampaui batasnya.
Wabakdu, hak suara setiap pemilih adalah bagian dari prinsip yang tidak ternilai. (*)