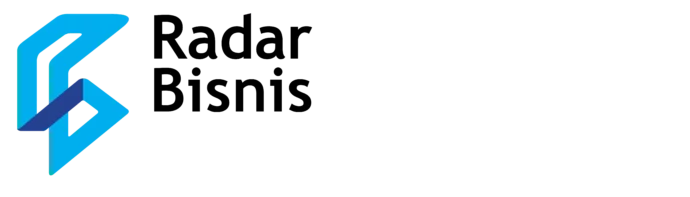LIMA tahun sekali, pemilu mengajarkan kita tentang roda kehidupan yang nyata. Bahwa hidup ini berputar. Ada yang cepat, ada yang lambat.
 Ketika menang, seketika berada di atas, dan ketika kalah, dengan cepat kembali ke bawah.
Ketika menang, seketika berada di atas, dan ketika kalah, dengan cepat kembali ke bawah.
Pun dari pemilu kita belajar bahwa keinginan untuk berkuasa dan mempertahankan kekuasaan telah menjadi paket tak terpisahkan dari jiwa manusia.
Ada adagium bahwa kekuasaan adalah candu—rasa ingin yang sulit lepas.
Terlebih, ketika sudah berada di atas. Sebisa mungkin diupayakan agar roda kehidupan ini tidak berputar ke bawah.
Fenomena ini mengingatkan pada pandangan Machiavelli tentang kekuasaan.
Baik secara sadar maupun tidak, setiap yang sedang berkuasa memiliki kecenderungan untuk mempertahankan kekuasaannya selama mungkin.
Lebih lanjut, Machiavelli memberikan pandangan, mereka yang sedang berkuasa akan mengerahkan segala sumber daya untuk mempertahankan kekuasaan.
Jika perlu, menggembosi kekuatan lain yang potensial untuk menjatuhkan.
Lebih keras dari itu, menurut Machiavelli, sekalipun mereka sadar bahwa kematian akan melucuti semua kekuasaannya, ia akan tetap berupaya keras untuk mempertahankan.
Di antara caranya, tegas Machiavelli, adalah mengukuhkan keturunan atau kongsi politik yang dapat menjaga kepentingannya.
Saban pemilu—dari dulu hingga kiwari ini, begitu banyak politisi yang serujuk dengan pandangan Machiavelli tentang kekuasaan.
Dan setiap orang berpotensi melakukan itu. Termasuk kita-kita.
Tidak ada jaminan bahwa ketika berkuasa akan berhenti pada periode yang dirasa sudah cukup.
Selama masih ada kesempatan, selamanya akan kita pertahankan. Jika perlu, kita ciptakan kesempatan-kesempatan baru untuk melanggengkan kekuasaan. Selama mungkin—tanpa batas waktu.
Ada sebuah anekdot, seorang presiden yang baru terpilih ditanya oleh wartawan, “Apa yang akan Anda lakukan setelah nanti resmi dilantik menjadi presiden?”
Si Presiden menjawab, “Saya akan memikirkan bagaimana cara mempertahankan kekuasaan di periode kedua.”
Machiavelli memiliki pandangan yang hampir serupa dengan anekdot tersebut.
Menurutnya, seorang raja akan terlebih dulu mengamankan kekuasaannya sebelum meraih tujuan lain, seperti sistem ekonomi rakyat, mengatur hubungan bilateral, ataupun merencanakan ekspansi negara (Fathur Rokhman-Surahmat, 2016).
Seorang kawan diskusi memiliki pandangan yang cukup netral ihwal kekuasaan.
Menurutnya, setiap orang memiliki kesempatan kedua untuk memperbaiki perbuatannya. Dia mengamini bahwa politik uang untuk meraih kekuasaan itu tidak dibenarkan. Apalagi menghalalkan segala cara.
Namun, baginya tidak menjadi masalah asal yang bersangkutan mampu memperbaiki perbuatannya ketika kekuasaan sudah didapat.
Dengan cara apa? Dengan cara menjalankan tugas dan tanggung jawab sebaik mungkin untuk kepentingan bersama—bangsa dan negara. Tidak melakukan hal-hal yang culas dan curang—mengkhianati rakyat.
Apa yang disampaikan kawan saya ini mengingatkan pada cara pandang yang disampaikan Gus Baha’(KH Bahauddin Nur Salim) ihwal politik uang yang diganti dengan diksi “membeli kebenaran”.
Politik uang dibolehkan asal tujuannya untuk kebaikan. Diksi “membeli kebenaran” yang disampaikan Gus Baha’ adalah dalam konteks ketika politik uang dilakukan oleh politikus saleh dengan tujuan untuk merebut potensi dikuasainya kekuasaan oleh orang zalim—yang sama-sama menggunakan politik uang untuk merebut kekuasaan.
Menurut Gus Baha’, jika demikian yang terjadi, maka tujuannya adalah “membeli kebenaran”.
Bagi saya, pandangan yang amat ideal itu cukup berat untuk bisa diwujudkan, tapi bukan berarti tidak bisa.
Dan saya sepakat, kesempatan kedua itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin—untuk memperbaiki diri.
Sudah menjadi rahasia jamak, hampir tidak ada peserta pemilu yang bebas dari politik uang. Dan saya pun sadar, tanpa money poitics hampir muskil terpilih. Sebab, rakyat kita belum sepenuhnya siap tanpa money politics.
Apa pun bentuknya, harus ada ganti suara yang telah diberikan.
Lantas, pesan apa yang bisa kita sampaikan kepada calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten, DPD, dan presiden-wakil presiden terpilih.
Tidak lain adalah memanfaatkan kesempatan kedua yang diberikan Tuhan.
Bagi saya, kesempatan kedua itu adalah ketika sudah dilantik nanti. Sebab, ketika anda gagal memperbaiki—menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik mungkin pada kesempatan kedua.
Maka, jika bukan rakyat yang akan menghukum anda pada pencalonan berikutnya, ingatlah! teramat mudah bagi Tuhan untuk menghukum kita.
Wabakdu, pemilu adalah gambaran roda kehidupan lima tahunan.
Karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk menyombongkan diri karena sudah terpilih.
Ingat! pemilu adalah roda kehidupan yang berputar setiap lima tahun sekali. (*)